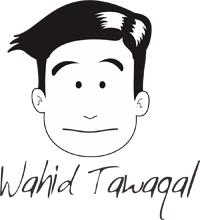Saya termasuk orang yang kalau jalan itu suka nunduk. Mata
suka melihat ke bawah. Itu jadi semacam kegemaran, soalnya ada banyak hal tak
terduga yang bisa saya lihat--yang gak bisa dilihat orang lain kalau jalannya gak
nunduk. Bentuknya sering seperti rejeki, saya pernah melihat bungkus permen tapi
isinya masih ada, nemu kelereng mata kucing dekat eek kucing. Tapi, di antara semuanya
yang paling sering itu: duit.
Duit memang sering banget. Saking seringnya nemu duit di
jalan mungkin jatuhnya udah kayak rejeki Tuhan yang diantar sama malaikat
Mikail. Tapi, bukan berarti uang yang saya temuin masuk kantong sendiri dan dikonversi
jadi es Segar Sari, gak gitu. Kadang juga uang itu saya ambil untuk dimasukkan
ke kotak amal di masjid.
Tapi rasanya itu sudah lamaaaaa sekali. Sekarang di tengah
kesibukan duniawi dan makin merasakan kejamnya menjadi dewasa, kebiasaan
mengambil ataupun mengantar duit ke kotak amal saat nemu di jalan seperti sirna.
Saya baru sadar soal itu setelah kejadian tadi sore.
***
Langkah kaki saya yang sedang menapaki koridor Student
Center, Unmul tiba-tiba berhenti. Di antara lantai ubin itu, ada kayu-kayu
balok tergeletak yang kalau diinjak tanpa alas kaki bisa telusupan. Kayu balok
itu gak jelas milik siapa dan fungsinya apa, tapi mata saya sukses memicing dan
menangkap warna cokelat di antara himpitan kayu yang juga warna cokelat. Rupanya di sana ada duit lima ribu kucel.
Malang sih, tapi jelas duit itu masih bisa dipakai.
Saya melupakan sejenak tujuan untuk segera ke sekretariat
LPM Sketsa Unmul yang mana sore tadi ada rapat, perhatian saya tertuju pada
duit lima ribu itu. Saya mengedarkan pandangan tapi tidak melihat ada
tanda-tanda kehidupan. Gak ada orang di sekitar situ dan saya juga gak melihat tanda
ini sebagai jebakan reality show.
Karena tidak ada orang, akhirnya muncul inisiatif baik untuk
mengambil uang itu dan menghibahkannya dalam bentuk sumbangan. Hitung-hitung
saya berbuat baik lah kepada yang duitnya kehilangan. Tuhan pasti suka sikap
mulia yang kayak gini. Sampai inisiatif baru muncul di kepala saya, kenapa
duitnya gak dibiarin aja? Maksudnya biar orang baik lain yang nemuin dan
nganterin duit itu ke masjid. Pilihan itu secara matematis jelas lebih mudah,
dan lagian pasti ada orang yang pengin berbuat baik. Nah, duit nemu yang gak
saya ambil bisa jadi jalan orang tersebut menuai pahala. Hitung-hitung saya
bikin orang baik senang.
“Ambil gak ya? Ah, gak usah aja deh,” kata saya ke diri
sendiri. Saya akhirnya memilih meneruskan jalan ke sekre LPM, tapi baru
beberapa langkah saya balik lagi buat ngecek duit itu.
Ada kemungkinan duit itu ditemukan oleh orang jahat. Dalam
kasus ini, dia tipe orang yang mengambil uang lima ribu dan membelikannya
Indomie plus Pop Ice rasa cokelat demi kenikmatan pribadi. Membayangkan itu
saya jadi takut sendiri. Saya kembali diam memandangi duit malang itu. Rasanya
pengin menjebloskannya jadi sumbangan tapi kok saya malas. Takut nanti saya
khilaf sehingga mengira duit itu milik saya dan membelikannya Indomie plus Pop
Ice rasa cokelat demi kenikmatan pribadi. Ternyata saya tak ubahnya orang jahat
versi saya sendiri.
Mendadak nemu duit jadi terlampau pelik. Kegemaran saya
jalan nunduk kok malah mengantarkan saya pada pilihan yang sulit. Hidup kok
gini amat. Pikir saya saat itu, saya harus menjadi lelaki. Dengan penuh
ketangguhan, saya katakan ini kepada duit lima ribu yang malang. “Saya ke atas
dulu nanti kalau kamu masih di situ, saya akan antar kamu.”
Saya lanjut jalan ke sekre LPM tanpa menoleh lagi.
Bagaimanapun duit itu harus bertahan sampai urusan rapat selesai jika dia memang
niat diambil orang baik yaitu saya sendiri. Sesampainya di sekre LPM, ada
beberapa anggota yang sudah berkumpul. Mereka tidak perlu tahu perdebatan batin
apa yang baru saya alami.
Sampai saya pulang, saya nyatanya tidak menepati janji. Saya
seperti lelaki kebanyakan yang omong doang. Saya lupa dengan duit lima ribu
itu, saya baru mengingatnya lagi ketika sudah berada di jalan pulang. Entah
bagaimana kabar duit itu sekarang, apakah dia ditemukan oleh orang yang jalan
nunduk juga atau malah ditemukan oleh orang yang jalannya hand stand? Saya beneran gak tau.
Yang jelas saya masih merasa benar karena gak mengambil duit
itu. Entahlah.